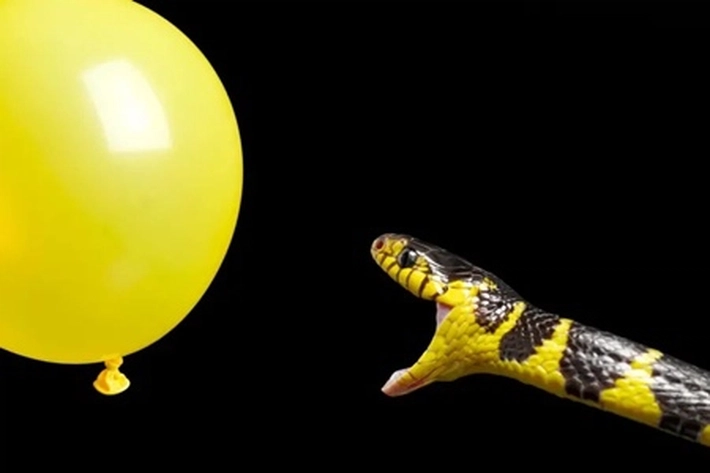
Gigitan Ular Berbisa Menimbulkan Kematian, Bagaimana Menanganinya?
RAFA, bocah usia 11 tahun asal Pekalongan yang sudah sebulan berjuang melawan bisa ular weling dilaporkan meninggal dunia, pada Minggu 20 Juli 2025.
Dia mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUP Dr Kariadi Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kuasa hukum keluarga Rafa, Imam Maliki, mengungkapkan insiden tragis itu terjadi pada 16 Juni 2025, dini hari. Saat itu, korban tengah tidur.
"Dari keterangan pihak keluarga ke kita, kronologis awal pada Senin (16/06) pukul 04.00 WIB. Adik RR sedang tidur. Ibunya kaget, karena ular melewatinya, kemudian ular menggigit anaknya," kata Imam kepada Detik.com.
Belakangan diketahui bahwa Rafa digigit ular weling. Ular tersebut, kata Imam, diduga terjatuh dari plafon rumahnya dan langsung menggigit korban.
Kejadian tersebut serupa dengan yang dialami Nurul Hidayah, warga asal Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur.
Dia sedang terlelap saat seekor ular menyelinap ke dalam rumahnya. Mungkin lantaran merasakan ada sesuatu yang merayap di dekatnya, dia lalu terbangun dan menyadari ada ular. Itu terjadi pada pukul 10.30 malam.
Kaget, dia lantas memanggil saudaranya untuk menyingkirkan ular dengan corak belang tersebut.
Ular belang itu bisa jadi ular welang atau ular weling. Keduanya berbisa dan banyak terdapat di Jawa.
Dua jenis ular itu dapat dibedakan secara sederhana dengan melihat pola belang di tubuhnya: welang punya corak belang hitam kuning, sedangkan weling hitam putih.
Oleh keluarga Nurul, ular belang itu tidak dibunuh, tapi disingkirkan ke luar rumah.
Nurul tak merasakan sakit apa pun setelah pertemuan dengan ular itu. Dia bahkan bisa kembali tertidur, hingga pukul 02.30 dini hari, lalu merasakan tak enak di seluruh tubuhnya.
Gigitan ular weling atau welang kadang-kadang memang sulit untuk divisualisasikan, menurut buku Pedoman Penanganan Gigitan, Sengatan Hewan Berbisa Dan Keracunan Tumbuhan serta Jamur yang diterbitkan Kementerian Kesehatan pada 2023.
"Saya bangunin kakak saya, kok rasanya begini," katanya.
Nurul ingat saat diantar ke rumah sakit. Tapi setelah itu, gelap. Dia tak sadarkan diri. "Saya nggak sadar selama 4 hari, di ICU 13 hari, lalu dipindah kamar sampai 26 hari."
Meski merasa belum sembuh benar, Nurul kemudian dibawa pulang dari Rumah Sakit Kertosono. "Tapi sebetulnya masih belum sembuh, masih tremor (gemetar) dan sering kejang, dua minggu di rumah lalu kembali lagi rumah sakit karena kambuh," katanya.
Seminggu dirawat, setelah itu ia disuruh pulang untuk rawat jalan.
Enam bulan berlalu. Perempuan ini mengaku kondisinya tak pernah kembali normal. Jantungnya kerap berdebar-debar.
Terakhir kali diperiksa, tekanan darah Nurul mencapai 101/77, dan denyut jantung 120. Ia juga mengalami kesulitan saat duduk, sulit berjalan, dan harus menggunakan kursi roda.
"Saya bingung dan akhirnya bekam, malah lebih parah, saya ingin cari obat dan cepat sembuh, harapannya seperti itu. Ini sudah tidak punya apa-apa, dijual untuk pengobatan. Saya ingin cepat sembuh, anak juga masih kecil-kecil," pungkas Nurul.
Kasus Nurul adalah satu dari 135.000 kasus gigitan ular per tahun di Indonesia – 10% di antaranya berakhir dengan kematian.
Jumlah yang tidak tercatat diperkirakan jauh lebih tinggi.
"Datanya kacau balau di sini, karena ada pasien gigitan ular yang berobat ke dukun, atau meninggal di rumah, tidak tercatat, itu banyak. Dalam kondisi begini, data kita tidak valid," kata dokter Tri Maharani, satu-satunya dokter di Indonesia yang punya keahlian di bidang racun bisa ular.
Bila kita mengetik "gigitan ular berbisa" di kolom mesin pencari, lalu menyaring dengan kategori berita, niscaya kita bisa menemukan ada saja korban gigitan ular dalam beberapa hari, pekan, atau bulan terakhir.
Akhir Juni lalu, seorang warga Subang, Jawa Barat ditemukan meninggal di tepi empang. Korban biasa mencari ikan dan telah dipatuk ular sebanyak tiga kali dalam kesempatan terpisah, kata keluarga. Patokan keempat itu berujung pada kematiannya.
Sejak awal tahun, setidaknya empat orang warga Suku Badui juga dikabarkan meninggal dunia akibat gigitan ular kata Ketua Sahabat Relawan Indonesia (SRI) Muhammad Arif Kirdiat. Mereka, di antara 36 korban patokan lainnya, terkena gigitan ular ketika hendak membuka ladang pertanian.
"Kami melaporkan sejak Januari sampai 22 Mei 2025, tercatat 36 warga Suku Badui Dalam dan Badui Luar yang menjadi korban gigitan ular tanah dan empat di antaranya meninggal dunia," katanya.
Jika ada masyarakat Badui yang terkena gigitan ular berbisa, kata dia, pihaknya meminta relawan bergerak cepat dengan merujuk ke RSUD Banten untuk menyelamatkan jiwanya.
"RSUD Banten memiliki serum ABU (antibisa ular) sehingga bisa ditangani dengan baik," katanya menambahkan.
Namun, data SRI berbeda dengan data yang dimiliki dokter Tri Maharani. Dia bilang terdapat satu kasus kematian warga Suku Badui di Provinsi Banten akibat gigitan ular sejak awal tahun.
Secara keseluruhan, Organissi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setiap tahun ada 5,4 juta orang yang tergigit ular, 2,7 juta di antaranya adalah kasus gigitan ular berbisa. Jumlah kematian berada pada rentang 80.000-140.000 kasus.
Kasus 'kesehatan masyarakat yang terabaikan (neglected public health issue)' juga mengakibatkan korban amputasi, atau disabilitas permanen lainnya. Kebanyakan korban adalah pekerja di bidang agrikultural dan anak-anak.
Para ahli memperkirakan jumlah spesies ular di dunia mencapai 3.700 hingga 4.000 spesies.
Sekitar 10% di antaranya, atau sekitar 349 spesies hidup di Indonesia, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari jumlah itu, hanya 77 jenis saja yang berbisa.
Secara umum, ada dua kelompok ular. Pertama, ular tipe wilayah Asia yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, serta Nusa Tenggara. Kedua, tipe wilayah Australia yaitu ular-ular yang hidup di sekitar wilayah Maluku dan Papua.
Tapi kata Amir Hamidy, peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, tidak semua jenis ular memiliki karakter yang khas yang dapat dikenali 100%.
Ular mampu berkembang biak dengan baik di sini, karena Indonesia berada di daerah tropis yang sangat hangat, lembab, cocok bagi ular untuk beranak pinak dan bertahan hidup.
Beberapa ular menghuni hutan-hutan nun di pedalaman. Sebagian lainnya menghuni apa yang disebut Amir sebagai "secondary forest."
Tapi ada spesies lain yang katanya harus diantisipasi. Ini adalah ular-ular yang telah beradaptasi dengan lingkungan manusia. Ular kobra Jawa adalah salah satunya.
Di Indonesia, konflik ular-manusia agak sukar untuk dipukul rata. Di hutan-hutan Maluku dan Papua, atau mungkin di Sumatra —yang mengandung 157 spesies atau hampir separuh total spesies di Indonesia—populasi dan spesies ular bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan daerah mana pun di Indonesia. Tapi tempat-tempat ini tidak lantas jadi episentrum konflik.
Pusat konflik itu malahan ada di Jawa.
"Karena di Indonesia ini hampir 60% penduduknya terkonsentrasi di Jawa. Jadi otomatis Jawa itu menjadi pusat potensi konflik terbesar terhadap ular berbisa," kata Amir Hamidy.
"Beda dengan wilayah Papua, walaupun spesies ular berbisa, mungkin lebih banyak di sana. Tetapi jumlah penduduknya dan kepadatan penduduknya tidak sepadat di Jawa".
Dari seluruh spesies ular terestrial (hidup di darat), di Jawa, kata Amir hanya 5% saja yang berbisa. "Mungkin hanya 13 jenis-lah ya (yang berbisa) di Jawa ini. Sisanya, 95% tak mengandung bisa yang berbahaya buat manusia alias aman-aman saja," tandasnya.
Tiga spesies yang paling banyak terlibat dalam konflik juga itu-itu saja, kata Amir: Kobra Jawa, ular tanah, dan welang.
Manusia dan ular telah hidup bersama sejak lama. Ular hidup dalam 'semesta' buatan manusia seperti sawah-sawah padi yang telah dipraktikkan di nusantara ribuan tahun yang lalu.
Mereka hadir sebagai 'sahabat' para petani dalam menjaga bulir-bulir padi dari serangan hama tikus.
Bahkan ketika sawah berubah jadi rumah, dan jalan-jalan tanah berubah jadi jalan beton ibukota, ular juga tetap setia mengikuti manusia.
"Katakanlah di Jakarta. Jakarta itu kurang apa padat apa? Padat penduduknya. Ular yang paling banyak apa? Kobra. Dan kobra itu bisa hidup di situ," kata Amir sembari menambahkan bahwa ular juga bisa beradaptasi karena makanan mereka juga ada di ekosistem kota.
"Kita sadar mereka nggak akan menghilang. Mereka habitatnya juga di situ."
Yang bisa kita lakukan adalah berbagi dan mengenali risiko bahayanya.
"Ular berbisa rata-rata aktifnya di malam hari, di mana tikus aktif di situ. Jadi secara ekologi waktu aktifnya pun berbeda. Kita aktif di siang hari, mereka aktif di malam hari," katanya.
Dia juga bilang, jarang ada orang bisa tergigit king kobra secara alami. "Rata-rata mereka (yang berisiko kena serangan adalah mereka yang) memelihara king kobra."
"Kalau ular tanah (masuk dalam golongan berbisa) memang paling banyak kejadian. Ular tanah itu berdiam saja di situ, dan mirip dengan daun, sehingga terinjak (baru mengigit," jelas Amir.
Gigitan ular bisa terjadi pagi atau siang hari, tapi kebanyakan serangannya terjadi malam hari. Oleh karena itu, menghindari kegiatan atau meningkatkan kewaspadaan di malam hari bisa meminimalkan risiko gigitan ular.
"Ular weling itu kan juga ada di sekitar kita, ya? Dan dia hidup malam hari. Dia bisanya sangat tinggi neurotoksinnya dan sangat cepat efeknya untuk melumpuhkan saraf."
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menghindari tidur di lantai, untuk risiko serangan ular yang melata.
Memelihara hewan peliharaan seperti kucing dan anjing juga bisa menjadi opsi. Hewan-hewan ini bisa menjadi semacam 'alarm' buat manusia.
Yang berikutnya, tidak bisa tidak, kita harus mengenali ular yang berbisa.
"Sebenarnya mengenali ular yang berbisa itu jauh lebih mudah daripada mengenali ular yang tidak berbisa. Karena (ular) yang berbisa ya hanya itu-itu saja," kata Amir Hamidy.
Ada beberapa ciri umum yang menandai apakah ular tersebut berbisa atau tidak. Uraian di bawah ini disarikan dari perbincangan kami dengan Amir Hamidy:
- Ular-ular berbisa memiliki kepala dengan bentuk segitiga, sementara yang tidak berbisa biasanya berkepala oval.
- Meski tidak selalu, ular-ular berbisa punya kecenderungan untuk memiliki warna yang mencolok.
- Kelompok ular berbisa tidak memiliki sisik di depan mata dan depan hidung langsung menempel.
- Ular berbisa memiliki taring di bagian mulutnya. Sebagian tersembunyi karena terlipat, sementara yang lain tidak.
Mengenali di mana pusat kesehatan terdekat juga krusial dalam kasus gigitan ular berbisa. Menurut WHO ada dua langkah paling cepat dan efektif dalam meminimalkan risiko gigitan ular berbida. Yang pertama adalah tidak menggerakkan bagian tubuh yang tergigit dan segera ke pusat kesehatan terdekat.
Selain datang ke pihak yang tidak kompeten, dokter Maharani juga mendapati banyak pertolongan pertama dan kegawatdaruratan tidak dilakukan dengan benar, sebagai akibat dari literasi yang rendah.
"Pada zaman dulu orang yang terkena bisa ular penanganannya dengan disedot, diikat kencang, akhirnya nekrosis, diamputasi," ucap Maharani. Tak jarang, penanganan yang keliru ini bahkan berujung pada kematian.
Padahal, menurut dia, pertolongan pertama adalah dengan membuat pasien tidak banyak bergerak atau imobilisasi.
Kebanyakan bergerak dapat membuat kontraksi otot yang mengaktifkan kelenjar getah bening. Inilah yang akhirnya membuat bisa menyebar.
Kata dokter Maharani, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa keracunan bisa ular hanya membutuhkan hitungan detik hingga menit sampai kepada kematian.
Berbeda dengan kanker atau serangan jantung – yang mendapatkan prioritas perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah – yang membutuhkan waktu relatif lama hingga tiba risiko kematiannya.
Ironisnya, ketika terdapat 135.000 kasus gigitan ular per tahun di Indonesia dan 10% spesies ular berbisa di dunia berada di Indonesia, penyediaan serum, termasuk semua rantai yang terlibat dalam pelayanan medis yang terkait dengan gigitan ular berbisa belum menjadi prioritas pemerintah.
Penawar racun ular, kata dokter Maharani, seharusnya disediakan oleh negara untuk warga yang terkena racun bisa ular. Hal ini pula yang menjadikan Maharani satu-satunya ahli di bidang bisa ular di Indonesia, karena negara belum memandang mendesak adanya pendidikan pada disiplin ilmu ini.
Beasiswa dan kesempatan belajar justru banyak didapatkan di luar negeri yang sudah lebih peduli dengan bahaya dan ancaman racun bisa ular. Maharani sendiri sempat berkeinginan membuat pendidikan toksinologi di Indonesia yang sangat dibutuhkan, namun tidak ada yang mendukungnya.
"Siapa mau riset sendiri, karena tidak dibayar? Sekolah pun saya bayar sendiri. Kurangnya dukungan yang nyata dari institusi negara dan masyarakat, menyebabkan tidak banyak orang yang mau belajar toksinologi. Menunggu pengertian mereka menjadi paham," terang Maharani.
Sebagai advisor WHO yang memiliki daya upaya yang tinggi terhadap penanganan kasus keracunan bisa ular ini, Maharani berharap Indonesia mengikuti negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menunjukkan perhatian dan dukungannya terhadap perkembangan toksinologi.
Bagaimana dokter Tri Maharani menjadi satu-satunya dokter ahli gigitan ular berbisa?
Pada 2010, dokter Tri Maharani kedatangan pasien, juga dengan keluhan gigitan gigitan ular berbisa. Menghadapi situasi itu, sebagai dokter biasa, dia akhirnya tersadar dan menerima kenyataan bahwa ilmunya mengenai keracunan bisa ular itu belum cukup.
Dia tak bisa berbuat banyak. Nyawa pasien melayang sebab bisa sudah telanjur kemana-mana.
Peristiwa itulah yang melecut dokter Tri untuk mulai mendalami ilmu tentang racun atau toksinologi yang dihasilkan oleh ular, hewan liar, atau tumbuhan lainnya.
Dia mengambil berbagai kursus dan sekolah lanjutan di luar negeri, memakai biaya pribadi, untuk memahami bagaimana tata laksana yang benar pada penanganan pasien dengan kasus gigitan ular berbisa serta racun hewan dan tumbuhan lainnya.
Pulang dari Belgia pada 2012, Maharani berkeliling ke nyaris seluruh wilayah Indonesia.
Dia menangani pasien, bekerja sama sama, berbicara, dan mengajari banyak tenaga medis dan instansi kegawatdaruratan untuk menangani pasien dengan kasus bisa ular.
"Ternyata masalahnya kompleks, pertama karena literasi bangsa kita yang kurang, dan kasus keracunan ini belum menjadi prioritas," kata Maharani.
Karena itulah dia juga memperluas kampanyenya dengan menyambangi komunitas-komunitas.
Di dunia, hanya ada 53 dokter dengan keahlian pada bidang emergency medicine, khususnya subspesialis toksinologi yang mampu menangani kasus bisa ular atau gigitan hewan berbahaya lainnya. Dokter Tri Maharani adalah salah seorang di antaranya dan satu-satunya pakar di Indonesia yang mendalami rumpun kesehatan tersebut.
Sejak 2014 Maharani rutin merogoh koceknya sendiri untuk membeli anti-bisa untuk menolong pasien-pasiennya. Katanya, hampir 90% serum antibisa yang dia pakai dibeli pakai uang pribadi.
Serum tak bisa dipakai serampangan katanya. Jenis bisa tertentu harus memakai penawar tertentu pula. Dan kata dokter Tri, tidak mudah untuk mendapatkan penawar racun itu. Kebanyakan juga dibuat di luar negeri, seperti Australia dan Thailand.
Di Thailand, pengembangan antibisa mendapat dukungan penuh dari Raja Thailand, kata Amir Hamidy, peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN.
"Thailand itu bisa memproduksi antibisa ular yang kering. Sehingga bisa sangat mobile (mudah ditransportasi). Dan itu bisa expired lima tahun. Sehingga harus disimpan di suhu ruangan pun tidak masalah.
"Sementara yang produksi kita harus ada di suhu empat derajat. Otomatis dalam mentransport harus dalam suhu yang dingin," tambah Amir.
Pemberian anti-bisa juga ditentukan oleh jenis ular yang menggigit, serta kesesuaian antara anti-bisa dengan bisa ular yang meracuni.
Secara umum racun bisa ular telah cukup tersedia di berbagai fasilitas puskesmas. Kata, Amir kondisi ini sudah cukup baik, bahkan jauh lebih baik dari 30 tahun yang lalu.
Indonesia sudah memiliki antibisa untuk tiga spesies ular yang paling banyak menyebabkan kasus gigitan yaitu kobra jawa, ular tanah, dan welang. Tapi itu bukan berarti PR-nya selesai. Ada beberapa spesies ular berbisa lain yang belum tersedia antibisanya.
"(Antibisa) kayak weling, terus ular-ular hijau, itu belum ada antibisanya," kata Amir.
Sementara itu, menurut dokter Maharani, Kementerian Kesehatan telah mengadakan antibisa melalui dana hibah sebesar Rp15 miliar setahun. Anggaran itu disediakan untuk melayani pasien BPJS di seluruh Indonesia.
Pada 2024 lalu Maharani bersama UGM telah berhasil membuat antibisa baru, yang pada 2025 ini akan segera diuji coba untuk produksi. Ia berharap akan ada antibisa-antibisa baru lainnya yang dibuat, khususnya yang selama ini hanya bisa diperoleh di luar negeri.
Saat berpindah tugas di Kementerian Kesehatan pada 2019, Maharani ditugaskan membuat buku pedoman terkait penanganan kasus bisa ular. Salah satunya mengenai pedoman keracunan alami dan non-alami.
Pada buku itu dijabarkan mulai antisipasi agar tidak tergigit ular, APD yang digunakan, pertolongan pertama, obat yang dapat direkomendasikan oleh dokter, hingga jenis ular dan fase yang dialami oleh orang yang tergigit ular.
Buku pedoman itu juga berisi foto-foto saat penanganan pasien kegawatdaruratan akibat tergigit ular maupun hewan berarun lainnya, misalnya ubur-ubur, kalajengking, semut, bulu babi, ikan pari, hingga tanaman dan jamur.
"Buku itu bisa jadi pedoman, masyarakat juga bisa memakainya, tapi untuk terapi tetap dilakukan oleh nakes atau named," kata Maharani.
Berbeda ketika orang tersengat ubur-ubur di laut, cukup diberi cuka untuk pertolongan pertama. Sedangkan bila tersengat tawon atau lebah tidak perlu memberi minyak atau param, cukup dengan memberi es batu pada bagian yang tersengat.
"Penanganan-penanganan itu tadi ada semua untuk pertolongan pertama, yang penting setelah itu harus segera menghubungi public safety center untuk kegawatdaruratan, misalnya di Surabaya 112, 119, kalau Jakarta 118," ujar Maharani.
Tidak hanya buku pedoman, masyarakat juga sudah dapat melakukan penanganan secara cepat dalam kondisi gawat darurat dengan memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan yaitu Virtual Poison Center.
Aplikasi ini akan memberikan banyak petunjuk dan cara penanganan kasus keracunan bisa ular dan hewan serta tumbuhan lain. Selain murah dan mudah diunduh pada perangkat digital, terdapat kontak ahli dan fasilitas kegawatdaruratan terdekat dari lokasi korban.
"Harapannya bisa segera terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Akan memudahkan bila ada bantuan virtual yang bisa diakses banyak orang," imbuhnya.
Bagaimanapun, dokter Tri Maharani masih menyimpan harapan bahwa pemerintah mendirikan Pusat Racun Nasional, yang didalamnya terdapat program gigitan ular.
"Soalnya belum ada pusat racun yang mumpuni," kata dokter Tri Maharani.
Menurutnya, infrastruktur ini begitu penting bagi rakyat Indonesia.
"Kalau [kena gigitan] ular, seseorang matinya cepat, bisa hitungan detik sampai menit," tutupnya. (*)
Tags : gigitan ular, ular berbisa, gigitan ular bisa timbulkan kematian, menanganinya gigitan ular, hewan-hewan, alam,





