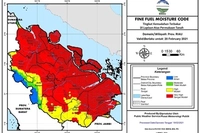Satgas PKH tak Sekadar Menguasai Kembali TNTN, 'Perlahan Satu per Satu Perambah Diproses Hukum'

PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tak sekadar menguasai kembali Taman Nasional Tesso Nasional (TNTN) dari para ‘perambah’.
Perlahan satu per satu, pemilik kebun skala luas atau kerap disebut cukong mereka panggil, minta menyerahkan kebun sawit ilegal, ada punya proses hukum.
Berbagai organisasi masyarakat sipil mengingatkan, penegakan hukum harus jelas dan tegas serta tak tebang pilih.
Tindakan itu mulai, sehari sebelum Satgas PKH menyegel kebun sawit dalam Tesso Nilo.
Tim ini terlebih dulu menahan dua alat berat yang sedang membuka areal buat tanam sawit baru, seperti Ervan Efendi dan Ramadhani.
Pasca Satgas PKH menyegel kebun sawit dalam taman nasional itu, giliran Polda Riau bergerak cepat menangkap Jasman, tokoh adat, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan.
Polda Riau menangkap Jasman, Batin Muncak Rantau, berselang 12 hari, setelah Satgas PKH memasang plang peringatan dan menanam pohon secara simbolis, pada 11 Juni 2025—langkah awal menghutankan kembali taman nasional itu.
Penangkapan Jasman lanjutan dari kasus Dedi Yanto alias DY. Polda Riau, lewat Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH), lebih dulu menangkap DY pada Februari lalu.
DY membeli 20 hektar lahan dalam TNTN dari Jasman. Transaksi jual beli tercatat dalam surat hibah adat dengan harga sangat murah, yakni Rp 10 juta.
Pria 54 tahun ini mengklaim punya hak ulayat 113.000 hektar.
Dia menjual pada lebih 100 orang.
Dalam konferensi pers di Gedung Media Center Polda Riau, 23 Juni lalu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, mengungkapkan, tidak anti terhadap kearifan lokal dan hak ulayat. Namun, dia ingin menunjukkan hukum adalah sebagai panglima tertinggi atas penyalahgunaan kewenangan.
“Kita harus bisa melakukan penegakan hukum, terhadap penyalahgunaan status adat untuk memperjual belikan kawasan konservasi yang notabene adalah rumah gajah,” katanya dikutip dari Instagram pribadinya.
Dia juga beri peringatan keras. Pengungkapan kasus jual beli hutan konservasi akan menyasar pada pelaku lain.
Menurut dia, itu tindak kejahatan terhadap keberlangsungan masa depan generasi penerus. “Saya tidak main-main. Kita akan tindak tegas.”
Dia juga mengingatkan TNTN adalah salah satu ekosistem atau kawasan pelestarian hutan paling vital di Sumatera.
Kelestariannya harus terjaga agar bisa menjadi paru-paru dunia, Pulau Sumatera, Riau, Pelalawan termasuk yang tinggal di sekitar kawasan konservasi itu.
“Kelestarian ini kita jaga demi kepentingan bersama. Bukan untuk oknum, sekelompok orang dan sebagian mereka yang mengklaim itu menjadi tanah ulayat dan lain sebagainya,” kata Herry.
Jasman tak seberuntung Nico Jan Andrio Sianipar dan Dedi Purnomo. Penguasa 401 hektar kebun sawit dalam TNTN, tepatnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan.
Setelah menyerahkan lahan pada Satgas PKH, tak ada penahanan pada dua orang ini.
Padahal, pada 24 Juni 2025, atau lima hari sebelum menyerahkan lahan resmi di lokasi, Polda Riau sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP).
Kejaksaan Tinggi Riau pun menerima surat itu. Keduanya terjerat UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE).
Pada hari penyerahan itu juga, 29 Juni 2025, Satgas PKH melalui Kementerian Kehutanan langsung menumbang sawit.
Nico mengakui megambil keuntungan dari sawit ilegal itu sejak 2006. Setelah itu, dia juga memulangkan pekerjanya.
Ade Kuncoro Ridwan, Dirreskrimus Polda Riau membenarkan menangguhkan penahanan Nico dan Dedi. Alasannya, dua perambah itu bersedia menyerahkan lahan secara sukarela.
Selanjutnya akan menumbang tanaman sawit dan reboisasi. Hal itu, mengacu pada Pasal 110 b UU Cipta Kerja.
Kabid Humas Polda Riau Anom Karibianto, mengatakan, kasus yang menjerat Nico dan Dedi selesai dengan penerapan azas ultimum remedium.
Pasalnya, kedua pelaku ini menyanggupi syarat yang tertuang dalam berita acara oleh Satgas PKH.
Selain Nico dan Dedi, Ketua Kelompok Tani Maju Suyadi, juga lepas dari jerat hukum. Dia anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Rokan Hilir lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekarang, dia bertugas di Komisi IV.
Suyadi menyerahkan kebun sawit 311 hektar dalam TNTN yang dia kelola bersama keluarga sejak 2009. Lokasinya juga di Desa Segati.
Sekitar 40.000-an sawit di atas kawasan konservasi ini. Usia tanaman paling muda berkisar satu tahun dan yang produktif 15 tahun.
Setelah menyerah kebun, awal Juli lalu, Satgas PKH langsung menanam pohon keras atau pohon hutan yang ramah satwa pada lahan itu.
Selain secara simbolis, penanaman ini lanjut oleh anggota kelompok tani. Suyadi hadir dalam prosesi ini.
Dia tak membalas pesan permintaan konfirmasi 11 Juli 2025. Dia juga tak menjawab panggilan ke nomor itu.
Dalam pemberitaan media lokal, Suyadi mengaku bersalah mengelola lahan baik secara pribadi maupun atasnama kelompok dalam taman nasional.
Dia membeli lahan bertahap, namun mengatakan tidak tahu status kawasan. Selain mengakui kesalahan, dia mengatakan telah menyelesaikan masalah ini dengan restorative justice dan cara damai.
Roni Sahputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, mengatakan, Polda Riau keliru menerapkan pasal 110B. Sebab ketentuan ini harusnya berlaku bagi pelanggaran yang terverifikasi, sebelum 2 November 2023.
“Nah setelah itu, jika tetap ingin diberlakukan maka dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administrasi dan pidana, yang dikenal dengan istilah kumulatif eksternal,” katanya melalui aplikasi perpesanan, 12 Juli 2025.
Pasal 110B bagi pelanggaran kegiatan berusaha atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak memiliki izin berusaha sebelum 2 November 2020.
Mereka kena sanksi berupa penghentian sementara kegiatan untuk penyelesaian izin. Lalu kena pembayaran denda atau paksaan pemerintah.
Roni bilang, subjeknya memang tidak memiliki izin sektor dan izin kehutanan tetapi pemberlakuan itu terbatas tiga tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku.
Lewat dari jangka waktu itu, seharusnya pemerintah melakukan tindakan hukum dengan sanksi pidana.
Aturan pelaksanaan Pasal 110B jelas pada PP 24/2021.
“Jikapun pemerintah memilih menjatuhkan sanksi lain, boleh. Yaitu, sanksi administrasi berupa pembayaran denda atau paksaan pemerintah,” katanya.
Dia juga menyebut pernyataan Suyadi menyesatkan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menyaratkan beberapa hal untuk penerapan mekanisme hukum itu.
Restoratif justice untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, hanya untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda bayar dengan sukarela, dan ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Hal itu dengan pertimbangan, subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. Kemudian, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana.
Selanjutnya, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan ada perdamaian antara korban serta tersangka.
Ada syarat lain. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta tindak pidana dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.
Dalam konteks TNTN yang merupakan kawasan konservasi, kata Roni, penegakan hukum harus langsung menggunakan jalur pidana.
Dia mengingatkan, larangan berkebun di kawasan konservasi sudah jelas dalam UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, maupun UU KSDAHE.
Pendekatan ultimum remedium, dengan sanksi pidana jadi opsi terakhir setelah sanksi administratif tidak berlaku dalam konteks perusakan kawasan konservasi.
“Ultimum remedium itu bukan otoritas penegak hukum untuk menafsirkannya. Itu domain pembentuk Undang-undang. Dalam kasus TNTN, sanksi pidana bisa langsung kena karena sudah diatur jelas dalam undang-undang.”
Difa Shafira, Kepala Divisi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), menjelaskan mekanisme penyelesaian melalui Pasal 110B hanya mungkin untuk sawit yang terbangun sebelum 2 November 2020.
Berdasarkan UU 18/2013 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan PP 24/2021, apabila sawit berada di hutan konservasi, maka wajib pengembalian kepada negara.
Ada dua hal perlu dipastikan. Pertama, pelaku betul-betul membayar denda administratif sesuai ketentuan dalam UU dan peraturan pemerintah.
Kedua, biaya untuk pengembalian fungsi hutan kepada pelaku. Terutama, apabila pelaku merupakan cukong, bukan masyarakat kecil.
Menurut Difa, ketidakpatuhan atas kewajiban pembayaran denda administratif dan pemulihan harus ditindaklanjuti dengan sanksi pidana.
UU 18/2013 dan UU 41/1999, sebenarnya masih membuka peluang untuk penegakan hukum pidana.
“APH (aparat penegak hukum) perlu memperjelas skema pilihan penegakan hukum agar konsisten dan tidak menjadi peluang main perkara.”
Difa mengkritik penggunaan istilah restorative justice dalam penyelesaian kegiatan usaha dalam kawasan hutan.
Bila memenuhi unsur tindak pidana, misal, ada sawit terbangun setelah 2 November 2020, seharusnya tetap proses pidana.
“Mekanisme yang melibatkan pengembalian sawit kepada negara itu bukan RJ (restorative justice). Melainkan mekanisme administratif yang harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110B UU 18/2013 jo. UU Cipta Kerja dan PP 24/2021,” jelas Difa, 12 Juli lalu.
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, cerobohnya proses penegakan hukum terhadap perambah TNTN, tak lepas dari Peraturan Presiden Nomor 5/2025, tentang penertiban kawasan hutan.
“Seburuk apapun norma di UU CK (Cipta Kerja), substansi perpres yang melampaui UU itu membuat proses penegakan hukum jadi sembrono dan abuse (penyalahgunaan atau perlakuan yang salah) dari presiden hingga kepolisian,” katanya 12 Juli lalu.
Dia sependapat dengan Roni dan Difa. Merujuk pada UU Cipta Kerja maka proses penegakan hukum pidana hanya bisa pada pekebun yang melakukan aktivitas setelah November 2020.
Jadi penetapan tersangka pada Nico dan Dedi, cukup janggal.
Boy bilang, yang harus sasar dari perambah TNTN adalah pengembalian aset, pemulihan dan pembayaran denda administrasi.
Selanjutnya, penegak hukum tidak boleh menyasar masyarakat pemilik lahan tidak lebih dari lima hektar dan telah beraktivitas lebih dari lima tahun.
Selain itu, proses pengembalian aset juga harus ada koordinasi untuk pembayaran denda dan kegiatan pemulihan.
“Bukan disiapkan untuk di take over ke Agrinas (perusahaan bentukan pemerintah buat mengurusi sawit sitaan kawasan hutan).”
Boy bilang, pengembalian kebun sawit dalam kawasan hutan harus melalui Kemenhut. Kenyataannya, Perpres 5/2025, lagi-lagi dia nilai merusak prosedur dan substansi.
Kalau berani dan semangatnya menegakkan hukum, kata Boy, sebaiknya presiden segera menerbitkan perppu untuk menghapus ketentuan Pasal 110B, kecuali ayat 2.
“Jadi aneh hukum kita pasca terbit Perpres 5 tahun 2025. perpres melampaui ketentuan Undang-undang. Kalau dibiarkan jadi preseden buruk dalam kontek per undang-undangan.”
Roni menilai, pendekatan pemerintah dalam menangani perambahan kawasan TNTN tidak tepat.
Dia menegaskan, pengambilalihan kebun sawit di kawasan hutan tidak bisa hanya mengandalkan kesukarelaan pelaku, tetapi harus melalui proses penegakan hukum jelas dan tegas.
“Seharusnya, pendekatan adalah penegakan hukum, bukan sekadar meminta pelaku menyerahkan lahannya secara sukarela,” katanya.
Selain itu, persoalan serius akan muncul pasca pengambilalihan kebun sawit di dalam kawasan TNTN jika tidak disertai pemulihan.
Logikanya, kawasan itu harus kembali ke fungsi asalnya sebagai hutan.
“Tapi siapa yang akan menebang sawit dan menanami kembali? Negara tidak akan sanggup menanggung semua biaya itu. Seharusnya perusahaan atau pelaku yang sudah mendapat keuntunganlah yang bertanggung jawab untuk memulihkannya,” ujar Roni.
Auriga mencatat, jika kawasan tidak pulih, akan menimbulkan masalah baru di masa mendatang.
Biaya pemulihan hutan, kata Roni, sangat besar dan harus ditanggung oleh pihak yang selama ini dapat untung.
Dia menekankan, dasar hukum pengambilalihan lahan di kawasan hutan harus mengacu pada UU Kehutanan atau UU Cipta Kerja, dengan opsi penindakan melalui jalur pidana, perdata, atau administrasi.
“Kalau hanya penyerahan tanpa disertai denda dan kewajiban pemulihan, maka prosesnya tidak selesai. Dan ini bisa jadi preseden buruk.”
Roni juga mengingatkan, sanksi tidak hanya pada korporasi, tetapi juga individu yang terlibat. Namun, identifikasi terhadap pelaku harus jelas.
“Jangan sampai pemodal besar yang bukan masyarakat adat, lalu mengklaim sebagai warga lokal untuk menghindari sanksi,” katanya.
Dia contohkan, jika pelaku adalah anggota dewan yang bukan masyarakat tempatan, seharusnya sanksi pidana, bukan hanya administratif.
“Apalagi kebun sawit di TNTN sudah besar, sudah panen, dan sudah menghasilkan keuntungan tanpa membayar pajak. Itu jelas merugikan negara.”
Menurut dia, negara kehilangan banyak dari perusakan kawasan konservasi seperti TNTN, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya habitat satwa langka seperti gajah, hingga hilangnya potensi penerimaan negara.
Karena itu, penegakan hukum harus tetap jalan meskipun pelaku sudah menyerahkan lahan secara sukarela.
“Tidak ada istilah sukarela kalau sudah merusak dan mengambil keuntungan dari kawasan konservasi. Harus tetap diproses hukum.”
Dia juga mengkritik kinerja Satgas PKH yang pasif dan terlalu administratif.
Menurut dia, penelusuran terhadap keberadaan kebun ilegal sebenarnya sangat mudah jika satgas mau membuka data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kini Kementerian Kehutanan, KATR/BPN, serta instansi terkait lain.
“Apalagi sawit itu tidak mungkin diolah sendiri. Pasti dikirim ke perusahaan tertentu. Penegak hukum seharusnya bisa menelusuri itu dengan cepat,” katanya.
Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari, mendukung penegakan hukum terhadap cukong yang menguasai sawit ilegal skala luas hingga ratusan hektar.
Begitu juga terhadap pemilik dan operator alat berat dalam kawasan hutan.
“Bagi cukong tidak ada ampun. Pulihkan dulu (kawasan hutan) yang dikuasai cukong. Masyarakat kecil dengan jangka benah. Masyarakat yang betul-betul dengan kepemilikan sawit terbatas. Dengan identifikasi terlebih dulu asal-usul kepemilikan lahan,” katanya, 6 Juli lalu.
Dia juga mendesak penegakan hukum menyasar pabrik sawit penerima buah sawit dari TNTN. Menurut Okto, pabrik di bawah kendali perusahaan punya pengetahun dan modal, hingga layak terjerat hukum.
Menurut Okto, PKS di sekitar TNTN adalah penyebab utama laju deforestasi kawasan konservasi itu.
Merujuk laporan Eyes on the Forest, Koalisi WWF Indonesia Program Sumatera Tengah, Jikalahari dan Walhi Riau, berjudul Cukup Sudah, 2018, ada 22 PKS yang menampung buah dari taman nasional tersebut.
“Perlu ditindak juga hukum PKS yang menerima buah. Termasuk dari PKS, mengalir ke grup perusahaan apa? Kalau sawit cukong ditebang, PKS juga harus bisa ditutup untuk menerima buah dari TNTN”. (*)
Tags : hutan indonesia, Masyarakat Adat, sawit, riau, sumatera ,