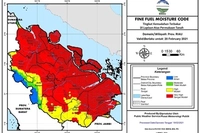World Food Day Nilai Sampah Dianggap 'Tidak Penting', 'Bisa Jadi Kompos Rumahan Hingga Budidaya Maggot'
LINGKUNGAN - Sampah makanan, yang jumlahnya nyaris separuh dari total sampah nasional, nyatanya masih sering “dianggap tidak penting” saat orang sibuk membicarakan daur ulang sampah plastik. Inisiatif bermunculan dari individu dan komunitas untuk mengatasi problem sampah makanan. Bagaimana peran pemerintah?
“Orang bilang ini bau sampah, tapi ada juga yang tahu kalau ini aroma fermentasi. Kalau kami di sini bilangnya ‘bau duit’,” kata Markus Susanto sambil terkekeh.
Berbagai aroma menguar dari tempatnya berdiri. Yang paling kuat adalah bau masam dan bau busuk dari beragam sampah makanan. Sesekali, saat angin berhembus, tercium pula aroma kotoran ternak.
Markus tampak tak terganggu dengan segala bau itu. Begitupun sejumlah pekerja yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang tengah memberi makan ikan dan ayam, sementara yang lain mengurus kebun pisang dan singkong.
Terletak di Kabupaten Bekasi, kawasan seluas 16 hektare ini merupakan satu dari tiga ‘Pusat Bio-Konversi’ yang dikelola Markus. Di pusat seluruh kegiatan ini adalah peternakan maggot, organisme mirip belatung atau bernga.
Ini adalah larva dari lalat hitam (Black Soldier Fly—Hermetia illucens) yang dihasilkan pada metamorfosis fase kedua, setelah fase telur dan sebelum fase pupa.
‘Pasukan’ larva inilah yang bertugas memakan sampah makanan yang dikumpulkan dari hotel, restoran hingga pasar. Dalam sehari, Markus bilang maggot-maggot-nya bisa melahap 10 hingga 15 ton sampah makanan.
Di atas kolam-kolam berukuran 1x1 meter yang berisi sampah makanan, maggot menggeliat—mungkin jutaan jumlahnya. Hewan dengan tubuh putih kecoklatan dan panjang masing-masing sekitar dua sentimeter itu nyaris menutupi permukaan kolam.
“Sumber makanan maggot ini adalah sampah makanan yang proteinnya tinggi. Jadi sampah makanan jangan disia-siakan karena bisa menghasilkan protein dan pupuk,” ujar pria yang telah ‘bergumul’ dengan sampah selama satu dekade terakhir.
Maggot-maggot tersebut akan siap ‘dipanen’ dalam 15 hari, yang kemudian menjadi pakan bernutrisi bagi ayam dan ikan di sana.
“Dari satu ton sampah makanan, bisa dikonversi dan menghasilkan hingga 85 kilogram telur ayam. Bayangkan!” tukas Markus dengan semangat.
Tak hanya sebagai pakan ternak, pasukan maggot juga kemudian bisa diolah kembali menjadi pupuk organik, baik berbentuk cair maupun padat.
Oleh Markus, lahan di sekitar Pusat Bio-Konversi yang sebelumnya telah diratakan kembali sehat setelah rutin diberi pupuk dari maggot. Hasilnya terlihat, pisang-pisang di kebun Markus tumbuh subur.
Tandan-tandan pisang yang menggantung telah siap dipanen saat warnanya berubah kekuningan.
“Saya meyakini sampah makanan punya kesempatan kedua,” ujar Markus.
Pada Agustus tahun lalu, kebakaran besar yang berlangsung selama berhari-hari melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Polisi mengatakan penyebab kebakaran adalah puntung rokok yang masih menyala saat dibuang. Namun keterangan polisi juga menyebut gas metana yang ada di tumpukan sampah membuat api menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan.
Tempat pembuangan sampah atau landfill mengandung berbagai macam gas.
Metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) membentuk sekitar 90-98% di antaranya, sementara sisanya adalah nitrogen, oksigen, ammonia, dan berbagai gas lain.
Metana, yang berasal dari proses dekomposisi bahan organik—seperti sampah makanan—oleh mikroorganisme di lingkungan yang kurang oksigen, sangat mudah terbakar. Bila bertemu dengan sumber api, gas ini juga bisa mengakibatkan ledakan.
Aliansi Zero Waste Indonesia mencatat, dari Juli hingga November 2023, setidaknya terdapat 38 kasus TPA yang terbakar karena ledakan gas metana yang dipicu cuaca panas. Memang, belum ada bukti yang menghubungkan semua kebakaran ini dengan metana.
“Dugaan orang selama ini, kebakaran dipicu karena ada yang membakar,” ujar Fictor Ferdinand, peneliti di program Zero Waste Cities dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB).
Namun, lanjutnya, secara saintifik, kuat dugaan gas metana ditambah panas kering karena kemarau menjadi faktor penyebab kebakaran sejumlah TPA di atas.
“Kalau kita ke TPA, selalu ada pemandangan tumpukan sampah dengan asap yang keluar dari tumpukan tersebut,” ungkap Fictor yang rutin mengunjungi berbagai TPA dalam lingkup kerjanya.
Ketika gunungan sampah itu diinjak, kata dia, pijakannya membal.
“Saya merasakan panas. Di udaranya dan dari dalam permukaan yang saya pijak. Lalu juga ada bayang-bayang fatamorgana,” tukasnya.
Ini semua, menurut dia, menandakan gunungan sampah itu menyimpan gas metana.
Kecurigaan ini diperkuat oleh data yang baru-baru ini dirilis oleh Carbon Mapper, sebuah organisasi nirlaba yang memantau timbunan gas metana dan karbon dioksida secara global menggunakan satelit.
Dalam pantauan mereka sejauh ini, tampak penumpukan gas metana di tiga titik Pulau Jawa dan semuanya berasal dari tempat pembuangan sampah: TPA Galuga di Bogor, Jawa Barat; TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten; dan TPA Cilowong di Serang, Jawa Barat.
Pada 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sebanyak 41% dari total sampah nasional adalah sampah makanan, yang sebagian besarnya bersumber dari rumah tangga.
Tak main-main, di seluruh Indonesia, sampah makanan beratnya bisa mencapai lebih dari 29 juta ton. Setidaknya butuh 969.280 kontainer dengan volume masing-masing 30 ton untuk mengangkut semua sampah makanan ini.
Jika diletakkan memanjang, seluruh peti kemas ini niscaya makan tempat hingga lebih dari 9.000 km. Ini lebih jauh dari jarak Sabang hingga Merauke.
Makanan hotel bintang lima di gang sempit
Di sudut Kota Surabaya, Jawa Timur, pada sebuah sore di hari Minggu, tampak antrean orang-orang membawa piring dan gelas kosong telah mengular.
Mereka sedang menunggu pada relawan Garda Pangan, organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang ‘bank makanan’. Mereka mengumpulkan makanan berlebih dari berbagai hotel dan restoran di Kota Surabaya.
Sore itu, menu yang tersedia antara lain ayam kecap, daging kari, dan berbagai jenis roti.
Qatrunnada Rafifa Zalfani, relawan Garda Pangan, telah mengumpulkan seluruh makanan itu sejak pagi.
Dia dan teman-temannya lalu memeriksa kelayakan makanan, menghangatkan yang masih baik, dan membagikan makanan yang telah dipastikan aman dikonsumsi kepada warga yang membutuhkan.
“Sekarang sudah ada 11 hotel bintang empat hingga lima yang bermitra, termasuk beberapa toko roti, produsen makanan dan minuman yang menjadi donatur rutin,” ungkap Qatrunnada.
Sejak 2017, Garda Pangan telah menyelamatkan 137 ton makanan berlebih yang berpotensi menjadi sampah makanan. Ini masih jauh dari angka total sampah makanan yang dihasilkan Jawa Timur yang mencapai sekitar tiga juta ton pada 2023.
“Karena keterbatasan kapasitas, kami baru bisa menyelamatkan sampai angka segitu,” tuturnya.
Angin semilir membawa aroma kompos dari bilik-bilik pengolahan sampah makanan di Perumahan Jatinegara Baru, Jakarta Timur.
“Aromanya seperti tape. Ada [aroma] asam yang enak, ada aroma manis. Bukan bau busuk,” kata Shanty Syahril, koordinator Koperasi Kompos di perumahan itu.
“Kalau dikelola dengan benar, sampah dapur itu ternyata enggak bau busuk. Seperti kita melakukan fermentasi,” imbuhnya.
Shanty memulai inisiatif mengompos di garasi rumahnya pada 2021. Saat hidup melambat karena pandemi, ia mengaku banyak orang mulai rajin berkebun, termasuk dirinya.
Dia juga mulai mengolah sampah makanan dari rumahnya sendiri. Lama-kelamaan, aktivitas ini dilakukan bersama-sama.
“Sampai 30 rumah bersedia untuk bergabung,” ujar Shanty, yang mengatakan komunitas ini berkembang begitu cepat, sampai-sampai garasi rumahnya tak lagi cukup untuk mengolah sebanyak itu itu sampah makanan.
Pada 2023, pihak RW setempat mengizinkan Shanty dan para ibu yang tergabung dalam Koperasi Kompos untuk menggunakan sebidang tanah yang kini menjadi ‘Taman Kompos’.
Jauh dari kumuh, taman yang ada di tengah-tengah perumahan itu tampak bersih dan rapi. Saat ini, dari 450 rumah yang ada di kompleks perumahannya, sudah ada 150 rumah yang berkontribusi. Dalam sepekan, setidaknya 500 kg sampah makanan dikumpulkan oleh pada pekerja Koperasi Kompos.
Memilah sampah dapur pun sudah menjadi kebiasaan dan tidak dianggap “ribet” di sini. Safroni, misalnya, punya tiga buah tempat sampah di dapurnya.
Satu tong untuk sampah organik seperti kulit buah dan sisa sayuran, satu tong untuk sampah plastik, dan satu tong lainnya untuk sampah kertas.
“Saya menanamkan pada anggota keluarga di rumah. Kalau kita buang begitu saja, kita hanya memindahkan sampah. Kalau dipilah, sampah organik jadi kompos, sampah anorganik bisa diterima pemulung,” bebernya.
Sampah organik dari warga ini kemudian dicampur ke dalam bilik-bilik tempat ‘memasak’ sampah makanan menjadi kompos. Dengan termometer, Shanty menunjukkan suhu sampah yang diproses itu menunjukkan 65-70 derajat celcius.
“Artinya, proses kompos sedang berlangsung,” kata Shanty.
Kompos yang dihasilkan kemudian dibagikan kembali sebagai pupuk untuk warga. Sebagian kecilnya dijual ke RW setempat untuk memupuk taman-taman komunal di perumahan.
Shanty mengakui, penjualan pupuk kompos ini tak seberapa. Dana operasional Koperasi Kompos pun masih berasal dari kocek pribadi Shanty dan para donatur. Namun, uang memang bukan tujuan utama dirinya membentuk inisiatif ini.
“Kalau ingin mengurangi sampah, yang harus dikelola itu sampah makanan. Selama ini yang ‘naik daun’ daur ulang dari bahan-bahan anorganik. Sampah makanan dipandang sebelah mata,” dia berujar.
Padahal, menurut dia, lebih mudah mencegah pemakaian sampah anorganik seperti plastik.
“Sementara kita tidak bisa hidup tanpa makan.”
Pemerintah Indonesia menargetkan sektor limbah dan sampah tidak akan lagi menyumbang emisi 26 tahun lagi. Ini ditandai dengan peluncuran dokumen Zero Waste Zero Emission 2050 yang di dalamnya terdapat peta jalan untuk mencapai target tersebut.
Salah satu langkah dalam dokumen itu antara lain soal pemilahan sampah dari sumbernya.
Menurut Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, pengolahan sampah makanan “seharusnya bisa selesai di rumah”.
“Manusia harus sadar bahwa kegiatan tiap individu menghasilkan sampah, termasuk makannya. Penting untuk memilah sampah di rumah, lalu mulai [belajar] melakukan kompos,” ujar Vivien seperti dirilis BBC News Indonesia.
Namun imbauan ini, menurut aktivis sampah Fictor Ferdinand, terdengar usang dan kadung terlambat.
“Seharusnya dilakukan 30 tahun lalu, sekarang TPA sudah penuh,” tandas Fictor.
Berkaca dari pengalaman pribadinya memberikan edukasi soal pemilahan sampah rumah tangga sejak 2017, warga hanya berubah perilakunya beberapa pekan saja.
“Selebihnya, perilaku masyarakat kembali seperti sebelum mereka mendapat pengetahuan tentang pengelolaan sampah,” katanya.
Alih-alih mengimbau, Fictor menekankan, pemerintah bisa berperan lebih tegas dalam penegakan hukum terkait sampah yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, mengakui bahwa penegakan hukum sudah dilakukan. “Tetapi ini tidak mudah,” kata dia.
Alasan utamanya, menurut Fictor, adalah masalah anggaran. Saat pengelolaan sampah diserahkan kepada pemerintah daerah, butuh komitmen besar dari daerah untuk mengalokasikan APBD mereka.
"Ada semacam 'perang' antara DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup [di bawah KLHK] suatu daerah," ucap Fictor, menggambarkan tarik ulur masalah anggaran pengelolaan sampah setiap kali rapat digelar.
Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, rata-rata anggaran daerah secara nasional untuk sub urusan pengelolaan sampah pada tahun 2022 hanya sebesar 0,51% dari total APBD.
Padahal, berdasarkan analisis Bank Dunia yang mengambil sampel dari 46 kota di seluruh dunia, pengelolaan sampah setidaknya mengambil porsi 4% dari total dana daerah—dan bila perlu persentasenya naik hingga 19% dari APBD.
“Menurut saya itu berat,” kata Novrizal, mengingat sekitar 70% anggaran daerah biasanya digunakan untuk belanja pegawai, pelayanan dasar seperti pendidikan, dan sisanya dibagi ke sektor lain.
KLHK sendiri mengusulkan agar kepala daerah mengalokasikan angka mendekati 3% dari total anggaran daerah, berdasarkan studi yang mereka lakukan di beberapa daerah yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang dinilai baik.
Jika dirasa kurang, Vivien mengusulkan pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah itu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
“Kita juga sekarang punya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup [BPDLH],” ujarnya.
BPDLH yang diluncurkan pada 2022 menghimpun dana di luar APBN dari berbagai sumber seperti Dana Reboisasi Hutan, Global Environment Facility, Bank Dunia, dan Amerika Serikat.
Hal lain yang juga berkaitan erat dengan masalah anggaran, adalah perihal tata kelola birokrasi. Selain anjuran KLHK, kata Fictor, butuh intervensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pedoman tegas soal pengelolaan sampah di daerah.
“Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk membangun infrastruktur [persampahan], tapi pemerintah daerah tidak punya uang untuk mengelolanya,” ungkap Fictor.
Padahal, bila tak ada inisiatif dari anggota dewan daerah, kelalaian pengelolaan sampah bisa menimbulkan risiko serius.
“Akhirnya jadi bom waktu, [misalnya] tempat pembuangan akhir kebakaran,” ujar Fictor.
Sejauh ini, KLHK mengaku sudah memetakan masalah anggaran ini berdasarkan data yang diterima dari tiap daerah.
Namun organisasi nirlaba Waste4Change mengkritik, belum ada standarisasi metodologi pengumpulan data di daerah, yang membuat validitas data di SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dipertanyakan.
"SIPSN itu sebagai kunci kami memetakan masalah, tetapi daerah terkadang memasukkan data yang hanya ingin terlihat bagus, setelah diverifikasi, ternyata datanya salah," ungkap Vivien.
Dalam akumulasi data sampah nasional itu, KLHK mengungkap sebanyak 107 kabupaten dan kota belum terintegrasi dalam sistem.
Merangkum segala permasalahan itu, Fictor berkata, “Masalah pengelolaan sampah ini merupakan masalah struktural.”
Meski demikian, Novrizal berharap inisiatif mandiri seperti yang dilakukan Markus, Shanty, dan Qotrunnada bersama komunitas Garda Pangan, menjadi contoh baik bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. (*)
Tags : Pangan, Bisnis, Gaya hidup, Indonesia, Lingkungan, Keamanan pangan,