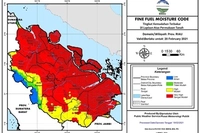Singkong Merupakan Lambang Identitas, 'Makanan Rakyat yang Berjasa'

SINGKONG adalah perlambang identitas. Dalam lagu pop tahun 1980-an, singkong dilambangkan anak kampung yang berbeda dengan keju, anak kota.
Di Asia, singkong menjadi andalan para petani, karena tanaman ini tahan kering dan bisa ditanam di lahan yang kurang subur sekalipun.
Di Brasil, pada abad ke-16, singkong jadi makanan pokok para budak dan tuannya. Tersedia melimpah di alam, singkong jadi andalan para budak yang melarikan diri.
Inilah yang membuat sejarawan mengaitkan singkong dengan perlawanan mengakhiri perbudakan di negara itu.
Aslinya, singkong berasal dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan selama 5.000-an tahun. Sebatang pohon singkong bisa menghasilkan akar yang gemuk-gemuk sampai beratnya mencapai 20 kilogram.
Karbohidrat yang dikandungnya terjaga dengan sempurna di bawah tanah. Bebas dari predator dan serangga berkat kulit tebal yang mengandung racun sianida.
Untuk menetralkan racun, akar mesti dikupas, ditendam, dibakar, dimasak, atau difermentasi dulu agar bisa dikonsumsi.
Singkong disajikan saat seorang ketua suku di Kepulauan Karibia menyajikan makanan mewah kepada Chistopher Colombus pada 26 Desember 1442.
Di Indonesia, singkong mungkin tiba bersamaan dengan kehadiran penjelajah Eropa. Tapi tak banyak sumber yang menyebutkan soal budi dayanya.
“Pertengahan abad ke19, di Demak ada kelaparan. Itu wabah yang luar biasa. Habis itu, tahun 1850-an seluruh residen Jawa dan Palembang dikumpulkan untuk diperkenalkan dengan sebuah tanaman, itulah singkong,” kata Haryono Rinardi sejarawan Universitas Diponegoro Semarang, penulis buku Politik Singkong Zaman Kolonial.
Singkong diperkenalkan sebagai jalan keluar dari krisis pangan. Tapi nyatanya, singkong malah lebih moncer sebagai komoditas dagang.
Hindia Belanda jadi produsen utama dunia. Tepung singkong diekspor untuk pangan, pakan ternak, lem, hingga industri kain.
“Di Prancis, gaplek diolah untuk menjadi minuman untuk pengganti anggur,” ujar Haryono seperti dirilis BBC News Indonesia.
Singkong tampil pada masa krisis.
“Ada lonjakan produksi ubi kayu yang luar biasa ketika kita menghadapi krisis. Krisis pertama itu ketika Perang Dunia I. Kita kena blokade Jerman,” lanjutnya.
Periode kedua adalah ketika Masa Depresi (Great Depression).
“Pedesaan Jawa menanggung beban karena pulangnya pekerja dari Sumatra Timur ke pedesaan. Itu kan butuh tanaman pangan yang mau tak mau bisa dimakan. Saat itulah ubi kayu nilai produksinya tinggi.”
Di Jawa, singkong tak cuma jadi pangan pangan alternatif selain padi, tapi juga sumber kreativitas camilan yang awet hingga sekarang dan jadi ciri khas daerah - menjadi identitas.
Jika mampir ke Kota Surakarta, ada panganan khas yang disebut lenjongan. Dan di Pasar Gede Solo ada penjaja camilan yang legendaris ini: 'Lenjongan Yuk Sum'.
Berbagai bentuk, warna, dan ukuran singkong yang telah diolah hingga memanjakan mata dan air liur.
“Itu jongkong. Cenil (juga) dari singkong. Tiwul dari singkong. Sawut dari singkong. Gatot dari singkong. Getuk dari singkong,” kata Yuk Sum yang telah berjualan di sana mulai dari 13 tahun.
Di Salatiga, ada produsen panganan singkong super empuk dan legit bernama Singkong Keju D-9.
Hardadi, pemiliknya, menisbahkan “D-9” nomor sel penjara tempat dia menebus kesalahan dan merenung pada nama usahanya.
“Di tahun 2009 itu saya pernah kena masalah narkoba. (Ditahan) di rutan kelas I Surakarta. Setelah keluar saya bukalah Singkong Keju D-9 ini,” kata dia.
Pada akhir pekan, ribuan orang bisa berkunjung ke toko yang berfungsi sebagai tempat makan juga.
Di sini puluhan menu camilan berbasis singkong dijajakan. Seruas jalan, dari ujung hingga ujung lainnya dipenuhi toko atau tempat makan yang menjajakan aneka panganan dari singkong.
Lengkap juga mural, bertema singkong. Semuanya bermula dari Singkong Keju D9 yang dibangun oleh Hardadi.
Kini, dia bisa mengolah kurang lebih lima ton singkong dalam sehari.
Dalam cerita sukses ini, Hardadi juga tak sungkan menyebut soal pinjam meminjam inspirasi.
“Jadi dulu di sini itu ada Gethuk Ketek. Itu karena masternya itu memang beliau,” kisahnya.
Dan sekarang berganti, Singkong Keju D-9 juga jadi modal usaha buat orang lain yang ingin meniru.
”Saya bilang pada teman-teman, sahabat D-9, kalian kalau sudah bisa bikin sendiri, mau bikin singkong keju maka saya persilakan. Dan alhamdulilah, di sini sudah ada puluhan merek singkong keju di sepanjang Jalan Argo Wiyoto ini.”
Memuliakan singkong
Di Kampung Adat Cirendeu, tak jauh dari pusat Kota Cimahi, Jawa Barat, singkong bukan semata-mata soal makan dan kesehatan.
“Ketika kita menanam, memanen, tidak asal nanam tidak asal manen. Sebelum manen kita ada Sanduk Papalaku atau berdoa, dengan membawa sesaji ke kebun singkong.
"Minta izin untuk dipanen,” kata Kang Yana, salah satu anak muda yang dipercaya tetua kampung untuk menjadi semacam humas Kampung Adat.
“Di sini kita lebih dikenal secara luas sebagai masyarakat adat Sunda Wiwitan. Kami dianggap unik oleh masyarakat di luar Cirendeu. Kalau kami biasa saja sebenarnya, karena kebetulan singkong menjadi makanan pokoknya,” sebut Kang Yana.
Warga Kampung Adat Cirendeu pada awalnya makan nasi. Tapi penjajahan dan perampasan bahan pangan memaksa para tetua berinovasi demi menyelamatkan adat.
“Jadi menurut para Pupuhu, kejadian tahun 1918 membuat sebuah upaya baru dari para tokoh untuk beralih (dari beras).”
Setelah uji coba enam tahun barulah mereka menemukan apa yang disebut rasi atau beras singkong. Rasi kering ini mampu bertahan lebih dari satu tahun jika disimpan dengan benar.
Rasi kini sudah ditetapkan jadi warisan budaya takbenda oleh pemerintah.
Singkong tak boleh ditanam di sembarang tempat, apalagi sampai merambah hutan larangan, itu dipegang teguh oleh warga Kampung Adat Cirendeu.
Ada falsafah Sunda, Tri Tangtu atau tiga ketentuan yang dipegang erat-erat. Sederhananya aturan ini adalah pembatasan wilayah sebagai penghormatan terhadap alam dan membatasi sifat rakus manusia.
“Pertama yang disakralkan yang tidak boleh diubah, apalagi ditanam singkong. Itu Leuweung Larangan. Kedua, Leuweung Baladahan, [ini wilayah] batasan antara yang boleh dan tidak boleh [dimanfaatkan].
"Yang bolehnya disebut wilayah Baladahan, itu tempat bertani atau budi daya,” kata Kang Yana lagi.
Pada 1985, tempat pembuangan akhir sampah dibangun di dekat kampung ini.
“Jadi otomatis kampung kami terisolir. Akhirnya (kami) jadi bahan ejekan orang lain. Masyarakat melabeli kami dengan Kampung Sampah. Ketika orang Cirendeu main ke kota, walaupun bukan seorang pemulung, pasti bau sampah karena pakaiannya pun nempel bau sampah yang sangat pekat.”
Pada 2005, sampah yang telah menggunung ambrol, longsor. Sebanyak 147 orang jadi korban. TPA lalu ditutup.
Dan inilah yang memberikan Desa Cirendeu napas yang telah direnggut sedemikian lama. Perlahan desa adat ini bersinar kembali. Jadi percontohan dan obyek liputan.
Kampung Adat pun ramai jadi sasaran wisata keluarga. Memanfaatkan kunjungan wisatawan atau warga yang berkunjung, kaum ibu kampung ini juga mengembangkan singkong jadi camilan enak.
Total ada tiga puluh lebih menu olahan. Antara lain eggroll cistik, cireng, lidah kucing, keripik bawang, opak bumbu, rasi goreng, dan lain-lain.
Singkong juga jadi bagian wisata edukasi. Terutama diniatkan agar para pengunjung mengerti apa yang mereka makan.
“Saya suka melihat di rumah makan, kok (makanan) nggak dihabiskan yah. Sayang yah. Dianggap sudah dibeli. Dianggap selesai dengan ekonomi, dengan uang. Padahal mah itu ada sesuatu yang secara spiritual.
“Kami membesarkan atau merawat tumbuhan itu dengan kasih sayang, dengan doa, dengan energi,” tutup Kang Yana. (*)
Tags : Pangan, Pertanian, Singkong, Lambang Identitas, Singkong Makanan Rakyat, Singkong Berjasa,